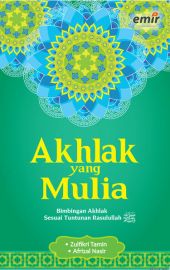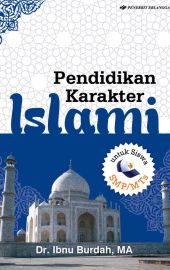Dalam Islam, berilmu dan bermoral atau berakhlak sama pentingnya. Karena itu, intelektualitas dan moralitas tak dapat dipisahkan. Memisahkan keduanya hanya akan membuahkan kehancuran.
Ketika Nabi Muhammad Saw. diutus kepada orang musyrik Mekkah, misi utama beliau bukanlah untuk mengajarkan baca dan tulis atau menanamkan kepandaian yang bersifat kognitif. Di antara kaum musyrik Mekkah telah terdapat bukan hanya orang yang pintar baca dan tulis, tetapi juga membuat syair dengan kadar sastra yang tinggi, bahkan dilombakan di antara mereka. Namun, diukur dari segala aspek, standar moralitas masyarakat jahiliah sangatlah rendah.
Dalam masyarakat Arab jahiliah, kecuali berasal dari keluarga terpandang perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua yang dapat diperlakukan kaum lelaki sebebasnya. Strata sosial masyarakat Arab Jahiliah juga lebih ditentukan faktor keturunan. Bahkan di antara klan yang satu dengan klan lain berbeda derajatnya. Fanatisme kesukuan yang sempit amat kental di kalangan Arab Jahiliah, sehingga definisi benar dan salah bergantung pada seberapa kuat satu suku beradu tanding di medan laga berhadapan dengan suku lainnya.
Akhlak terburuk masyarakat Arab Jahiliah tentu saja kemusyrikan mereka. Kemusyrikan yang mereka praktikkan bukan saja berbentuk paganisme atau penyembahan atas berhala, tetapi merasuk ke dalam cara pandang hidup yang cenderung mematerialkan segala hal dan menjunjungnya tinggi-tinggi. Sehingga hukum rimba pun berlaku. Mereka yang kuat, maka dialah yang menang dan berkuasa.
Dalam semua keadaan itulah, Nabi Muhammad Saw. diutus kepada masyarakat Arab Jahiliah dengan satu misi, sebagaimana termaktub dalam sabda beliau: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak” (HR. Al-Bukhari, no. 273; Ahmad II/381; Al-Hakim II/613)
Ketika Sayyidah Aisyah Ra. ditanya oleh Hisyam bin Amir Ra., seperti apakah akhlak Rasulullah Saw., ia menjawab: “Akhlak Nabi Saw. adalah Al-Qur’an” (HR. Muslim)
Jawaban yang diberikan Sayyidah Aisyah Ra. amat singkat, namun bermakna sangat dalam. Mengapa demikian? Karena Al-Qur’an adalah kitab petunjuk bagi umat manusia yang membuat mereka dapat membedakan mana yang benar dan salah (QS. At-taubah [9]: 33). Al-Qur’an juga merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah [2]: 2). Bahkan, Al-Qur’an juga menjadi kitab petunjuk bagi selain manusia (QS. Al-Jinn [72]: 13)
Karena itulah, Nabi Muhammad Saw. tak dapat dipisahkan dari Al-Qur’an. Sebaliknya, Al-Qur’an tidak dapat dipisahkan dari pribadi beliau. Apa yang termaktub di dalam Al-Qur’an, semua tergambar dalam pribadi, karakter, atau akhlak Rasulullah Saw. Semua perbuatan Rasulullah Saw. bersumber dari Al-Qur’an. Rasulullah Saw. pula yang menjelaskan kepada umatnya setiap kehendak Allah Swt. dalam firman-Nya yang termaktub di dalam Al-Qur’an.
Karena itu, semua hal yang bersumber dari Rasulullah Saw. mulai dari ucapan, perbuatan, dan sikap diam atau persetujuan beliau adalah wahyu yang tidak melenceng dari bimbingan Allah Swt. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Najm [39], ayat 3-4: “Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.” Semua hal yang bersumber dan disandarkan kepada Rasulullah Saw. itulah yang dikenal dengan hadis. Jadi, Al-Qur’an dan hadis adalah dua sumber Islam yang tidak bisa dipisahkan.
Selanjutnya, dengan misi utama untuk memperbaiki akhlak manusia, Nabi Muhammad Saw. mengajarkan paket lengkap kepada umat dalam berakhlak, mulai dari cara berakhlak kepada Allah Swt., berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada lingkungan dan alam sekitarnya. Untuk mengetahui kesemua cara berakhlak itu tentu saja harus mengetahui ilmunya. Sebab, Nabi Muhammad Saw. mengetahui semua ilmu akhlak tersebut, yang dibimbing langsung oleh Allah Swt. dengan perantaraan malaikat Jibril As.
Dalam kaitan itu, menuntut ilmu menjadi wajib karena hanya dengan cara itu maka tujuan berakhlak dapat tercapai. Artinya, ilmu merupakan wasilah atau sasaran antara yang dapat mengantarkan seseorang pada tujuan akhir. Lantaran hal ini pula, orang yang berilmu dihargai beberapa derajat lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu telah berusaha untuk menggali mana yang benar dan salah, yang dari sana akan menjadikannya sebagai orang yang berakhlak dan bijaksana.
Akan tetapi, orang yang berilmu tidak lantas membuatnya langsung menjadi baik. Sebab lagi-lagi ilmu adalah sebatas alat. Ia adalah penerang, dan penerang itu tidak akan memberikan sinar bagi yang memilikinya, jika pemiliknya selalu mendekati kemaksiatan. Hal ini dialami sendiri oleh Imam Syafi’i, ketika suatu kali ia mengadu kepada gurunya, Imam Waki’ bin Jarah, ihwal hafalannya yang begitu buruk.
Imam Syafi’i mengatakan: “Aku mengadu kepada Waki’ perihal buruknya hapalanku, maka ia memberi petunjuk agar menjauhi maksiat. Dikatakannya, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan memberi petunjuk bagi pelaku maksiat” (Imam Fakhrurrazi, Manaqib Asy-Syafi’i/44)
Apa yang diungkapkan oleh Imam Waki’ merupakan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah ayat di dalam Al-Qur’an, sebagai berikut: “Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 5)
Demikianlah, manakala ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tidak dioperasionalkan atau tidak diamalkan, maka ilmunya itu akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi bumerang baginya. Ibnu Ruslan Asy-Syafi’i di dalam Matn Zubad membuat syair indah begini: “Orang alim (berilmu) yang ilmunya tidak diamalkan, maka akan diazab sebelum para penyembah berhala diazab.”
Syair indah dari Ibnu Ruslan Asy-Syafi’i tersebut bukanlah pepesan kosong. Sebab syair itu merupakan kesimpulan yang dipahami dari ayat Al-Qur’an, surah Shaf [61], ayat 2-3, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”
Siapa orang yang berilmu?
Orang yang berilmu, namun ilmunya itu tidak menunjukinya kepada jalan yang lurus dan benar sejatinya tidak dapat dikatakan sebagai orang yang berilmu. Pendidikan yang dikecapnya boleh jadi tinggi, tetapi hal itu tidak membuatnya bijaksana dan mawas diri. Orang yang seperti itu justru akan semakin jauh dari kebenaran, sekalipun secara lahiriah ilmunya bertambah.
Dari Anas Ra., dari Rasulullah Saw., beliau berpesan: “Barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk (hidayah), niscaya dia tidak bertambah dekat melainkan bertambah jauh dari Allah” (HR. Ad-Dailami; Ibnu Hibban; al-Fawa’id al-Majmu’ah lis-Syawkani/742)
Ketika menjelaskan hadis tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyitir banyak pendapat para ulama, di antaranya sebagai berikut.
(Sayyidina) Umar Ra. berkata: “Yang paling saya takutkan kepada umat ini adalah orang munafik yang berilmu. Para hadirin bertanya, ‘Apakah ada orang yang munafik berilmu?’ Umar Ra. menjawab: ‘Mereka adalah yang berilmu di lidah, tetapi bodoh di hati dan di perbuatan’.”
Suatu kali Ibrahim bin Uyainah ditanya: “Manakah manusia yang lama benar penyesalan nya?” Maka ia menjawab: “(Orang seperti itu) di dunia ini adalah yang berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Sementara orang yang kedua adalah orang berilmu, namun ia mati dalam keadaan menyia-nyiakan ilmunya.”
Al-Khalil bin Ahmad mengatakan: “Orang itu ada empat macam. Pertama ialah orang yang tahu bahwa ia tahu. Itulah orang yang berilmu, maka ikutlah ia! Kedua adalah orang yang tahu, tetapi ia tidak tahu bahwa ia tahu. Ia adalah orang yang sedang tidur, maka bangunkanlah ia! Ketiga ialah orang yang tidak tahu, dan ia tahu bahwa ia tidak tahu. Orang jenis ini adalah orang yang membutuhkan petunjuk, maka berilah ia petunjuk! Ketiga, adalah orang yang tidak tahu, tetapi ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu (sok tahu). Orang ini adalah orang yang bodoh, maka tolaklah ia!”
Sementara Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa: “Ilmu itu disusul dengan amal perbuatan. Jika seperti itu, maka ilmu itu menetap (pada diri seseorang). Akan tetapi, jika tidak (disertai perbuatan), maka ilmu itu pergi.”
Akhir kata, Islam adalah perwujudan dari iman, ilmu, dan akhlak yang mulia atau moralitas yang tinggi. Jika seorang Muslim tidak menunjukkan ketiga hal itu, maka secara substantif, keberislamannya telah tercerabut dari dirinya. Seseorang boleh mengaku Muslim, tetapi jika perilakunya tidak bermoral, maka secara hakiki ia bukan lagi Muslim. Wallahu alam bish-shawab. (@abumubirah)